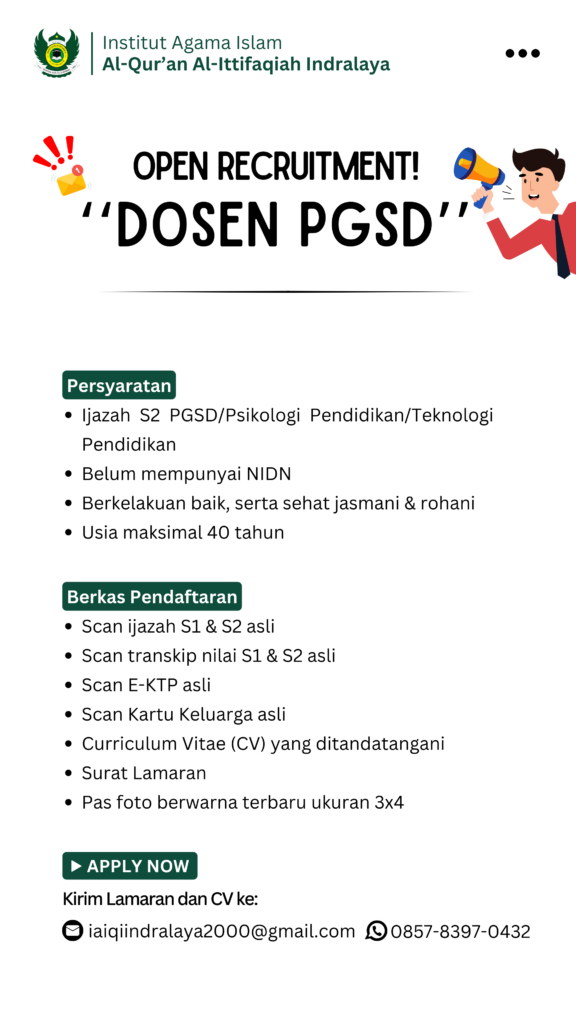Darmaningtyas*
Sertifikasi sebagai tanda standardisasi produk itu diperlukan untuk sebuah proses produksi (manufaktur), tapi tidak tepat untuk diterapkan dalam pendidikan dan kebudayaan; mengingat input maupun orientasi input-nya amat beragam. Korporasi dalam pengertian yang sederhana adalah perusahaan besar yang dipisahkan antara manajemen dan kepemilikan sahamnya.
Perusahaan-perusahaan besar yang disebut korporasi tersebut pada umumnya dikelola secara profesional, oleh orang-orang profesional, dan dengan standar pengelolaan (manajemen) yang baku dan ditandai dengan sertifikasi ISO atau sejenisnya. Sertifikasi semacam itu bagi mereka penting karena melambangkan tingkat keprofesionalan. Terlebih bila perusahaan tersebut adalah jasa konsultansi atau penyuplai produk ke instansi lain, yang untuk mendapatkannya harus melalui sistem tender.
Persyaratan tender biasanya beragam, termasuk kepemilikan sertifikat. Semakin banyak jenis sertifikat yang dimiliki dan berasal dari luar negeri, probabilitas untuk menang semakin tinggi. Sertifikasi dalam pendidikan Pola pikir sertifikasi ini sekarang ini tidak hanya terjadi di dunia swasta, tapi juga telah merasuk ke dunia pendidikan dan kebudayaan. Inilah yang disebut sebagai pola korporatisasi pendidikan dan kebudayaan; yaitu menjadikan pola manajemen di korporasi sebagai acuan untuk pengembangan manajemen institusi pendidikan. Padahal keduanya berbeda, karena yang satu mencari untung (profit center), dan yang satunya lagi menghabiskan dana (cost center).
Konsep sertifikasi dalam dunia pendidikan itu pada awalnya diperkenalkan sebagai upaya untuk menciptakan standardisasi (produk). Semula konsep sertifikasi tersebut hanya diperuntukkan bagi guru dan dosen untuk memperoleh pengakuan sebagai tenaga profesional yang diikuti dengan pembayaran tunjangan profesional. Tapi, kemudian, program sertifikasi guru dan dosen ini diikuti dengan program sertifikasi manajemen, seperti misalnya sertifikasi ISO 9001:2000 atau ISO 14000 versi terakhir. Jadi, pada saat ini bukan hanya guru dan dosen yang berburu sertifikat, lembaga sebagai pengelola pendidikan pun berburu sertifikat (ISO) agar sekolah/kampus mereka disebut modern. Kecenderungan standardisasi dan sertifikasi dalam dunia pendidikan itu sepintas membanggakan, tapi bila ditelisik lebih dalam lagi amat mencemaskan kita, karena akan membawa pengelolaan pendidikan dalam roh korporasi: steril, kaku, dan monoton. Padahal dunia pendidikan seharusnya variatif, inovatif, dan dialogis.
Standardisasi memang diperlukan dalam suatu proses produksi guna mengukur tingkat efisiensi produksi. Dengan adanya standardisasi yang baku, suatu proses produksi dapat disebut efisien/ tidak bergantung pada hasil akhirnya. Misalnya, dalam percobaan, 100 kg terigu setelah dicampur dengan bahan baku lain dan diolah menghasilkan 1.500 bungkus mi instan dengan berat 72 gram. Bila dalam proses produksi selanjutnya ternya ta bahan baku yang sama menghasilkan kurang dari 1.500 bungkus mi instan, berarti terjadi inefisiensi dalam proses produksinya.
Standardisasi itu diperlukan agar langkah-langkah produksi yang terjadi pada saat percobaan dan menghasilkan 1.500 bungkus tadi dapat dibakukan dan menjadi pedoman proses produksi berikutnya untuk menghasilkan produk yang optimal. Tapi standardisasi semacam itu hanya mungkin bisa dilakukan bila bahan bakunya sama, jenis peralatan yang digunakan sama, orang yang memproduksi punya kemampuan selevel, serta proses produksinya sama. Bila salah satu komponennya tidak lengkap, standardisasi tersebut tidak bisa dilakukan. Jadi, standardisasi itu hanya bisa dilaksanakan dengan akurat bila seluruh komponennya sama.
Berdasarkan pemahaman standardisasi seperti itu, maka standardisasi tunggal dalam pendidikan yang ditandai dengan sertifikasi ISO 9001:2000 atau ISO 14000 versi terakhir adalah suatu kemustahilan. Sebab, dapat dipastikan bahwa input, prasarana dan sarana, kualitas pengelola, kultur yang melingkupi, maupun masyarakat pendukungnya berbeda-beda, tidak sama persis. Dalam kasus 100 kg terigu, dengan proses produksi yang sudah distandardisasi akan dihasilkan 1.500 mi instan dengan berat 72 gram per bungkus. Tapi, jika 240 murid baru di suatu SMA favorit yang memiliki IQ rata-rata di atas 120 diajar dengan materi yang sama dan oleh guru yang sama, belum tentu hasilnya sama. Ternyata dari 240 murid tersebut ada yang berminat menjadi dokter, insinyur sipil, insinyur mesin, psikolog, arsitek, jurnalis, seniman, ilmuwan, pengusaha, dan pekerja sosial. Hasil seperti itu bukan suatu kegagalan, tapi memang itulah fakta bahwa manusia itu makhluk misteri, tidak bisa dicetak untuk hanya satu tipe produk tertentu saja.
Mengingat manusia itu makhluk misteri, serta minat dan orientasinya dinamis, maka proses pembentukannya tidak bisa distandardisasi secara tunggal, apalagi disertifikasi. Mensertifikasi proses pembentukan manusia melalui lembaga pendidikan formal sama saja dengan menciptakan korporatisasi dalam dunia pendidikan.
Hasil akhirnya belum tentu suatu prestasi gemilang, melainkan justru kegagalan yang fatal. Menjadikan sertifikasi ISO sebagai ukuran keberhasilan manajemen pendidikan jelas merupakan langkah yang sesat. Justru model-model pendidikan ala pesantren yang menerapkan sistem sorogan atau bandongan dulu relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Sertifikasi seniman Kecenderungan korporatisasi itu tecermin pula pada pengembangan budaya. Gagasan Wakil Menteri Pendidikan Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti, untuk mensertifikasi seniman dengan alasan agar dapat bersaing dengan seniman dari luar negeri, terutama negara-negara maju, adalah contoh konkret dari korporatisasi budaya.
Gagasan ini sesat dari dua hal. Pertama, sebutan “seniman“ sejak dulu kala tidak pernah ditandai dengan selembar sertifikat, termasuk ijazah, melainkan merupakan pengakuan dari proses panjang pergulatan ide dan perbuatan seseorang untuk menghasilkan karya seni yang dapat dinikmati oleh publik, tanpa mempedulikan ijazah sang seniman. Seseorang yang mengantongi sertifikat (ijazah) dari Institut Seni Indonesia (ISI) tidak secara otomatis disebut seniman bila dia tidak memiliki karya yang dapat dinikmati publik. Dia hanya disebut sarjana seni. Sebaliknya, meskipun seseorang itu tidak memiliki selembar ijazah dari perguruan seni, ia disebut seniman bila karyanya mendapat apresiasi publik.
Kedua, seniman berkarya untuk mengekspresikan gagasannya, bukan untuk bersaing dengan siapa pun. Seniman lebih suka berkolaborasi dengan pihak lain untuk menghasilkan karya spektakuler/ monumental, daripada bersaing dengan sesama seniman. Karena gagasan mensertifikasi seniman itu merupakan gagasan yang sesat, ia tidak perlu dilaksanakan di lapangan, apalagi dibuat kebijakan khusus. Kembalikan seniman itu pada proses kreatifnya. Jadi, kesimpulannya, sertifikasi sebagai tanda standardisasi produk itu diperlukan untuk sebuah proses produksi (manufaktur), tapi tidak tepat untuk diterapkan dalam pendidikan dan kebudayaan; mengingat input maupun orientasi input-nya amat beragam. Pengelolaan dan pengembangan pendidikan serta kebudayaan jauh lebih tepat didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat setempat. Pendidikan dikelola secara dialogis, dan seniman didorong produktif sesuai dengan proses kreatifnya; bukan dengan mensertifikasi.
*Penulis Buku “Manipulasi Kebijakan Pendidikan”
dari http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT